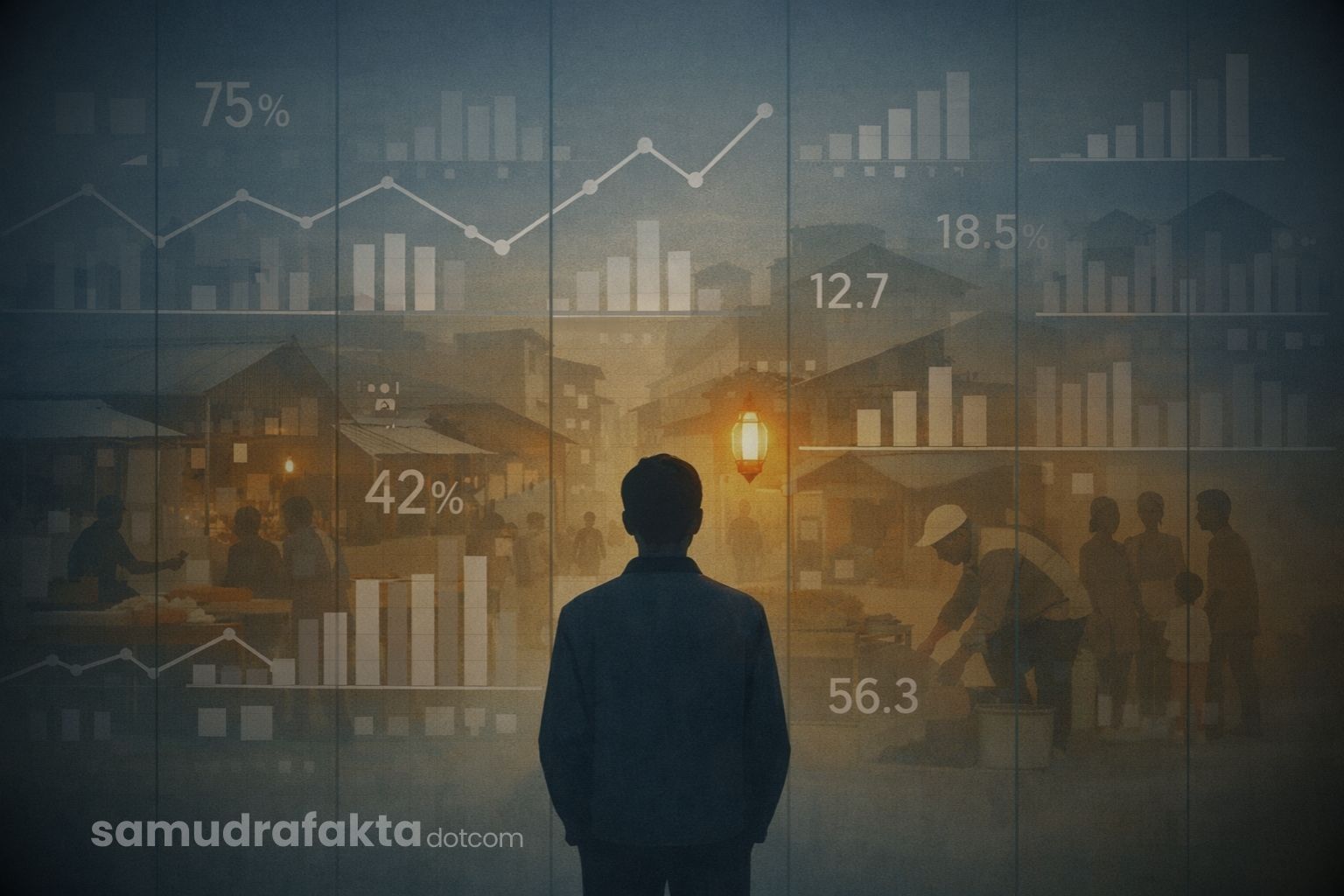Tak satu pun prasasti atau naskah kuno mencatat Perang Bubat. Sejarawan Agus Sunyoto menyebut kisah ini sebagai fiksi buatan kolonial Belanda untuk mengadu domba dua etnis besar di Nusantara.
__________
Kisah Perang Bubat telah lama hidup dalam benak masyarakat Indonesia. Kisah yang digambarkan sebagai tragedi berdarah antara Majapahit dan Kerajaan Sunda itu bahkan diajarkan di sekolah, dijadikan film, dan sering dijadikan alasan renggangnya hubungan historis antara orang Jawa dan Sunda.
Namun menurut sejarawan Agus Sunyoto (almarhum), semua itu tak lebih dari cerita fiktif yang sengaja disusun oleh kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah asli Nusantara, menurut Agus, peristiwa semacam itu tak pernah ada.
Agus menegaskan, tak satu pun prasasti Majapahit atau naskah kuno seperti Pararaton, Nagarakretagama, hingga babad asli yang memuat kisah pembantaian keluarga Sunda di Bubat. Bahkan, dari sisi Sunda, menurut Agus, bukti otentik yang menyebut tragedi serupa juga tak ditemukan.
Sumber satu-satunya yang menyebut tragedi Bubat hanyalah Kidung Sunda—sebuah naskah yang baru muncul sekitar tahun 1860, atau lebih dari lima abad setelah Majapahit berdiri. Agus menilai, waktu kemunculan ini mencurigakan, karena bertepatan dengan era kolonial yang sedang gencar mengukuhkan kekuasaannya.
Dari sinilah Agus melihat jejak politik adu domba. Setelah kekalahan telak Belanda dalam Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro, mereka sadar bahwa persatuan budaya dan etnis adalah kekuatan utama pribumi. Maka, narasi-narasi pemecah mulai diciptakan.