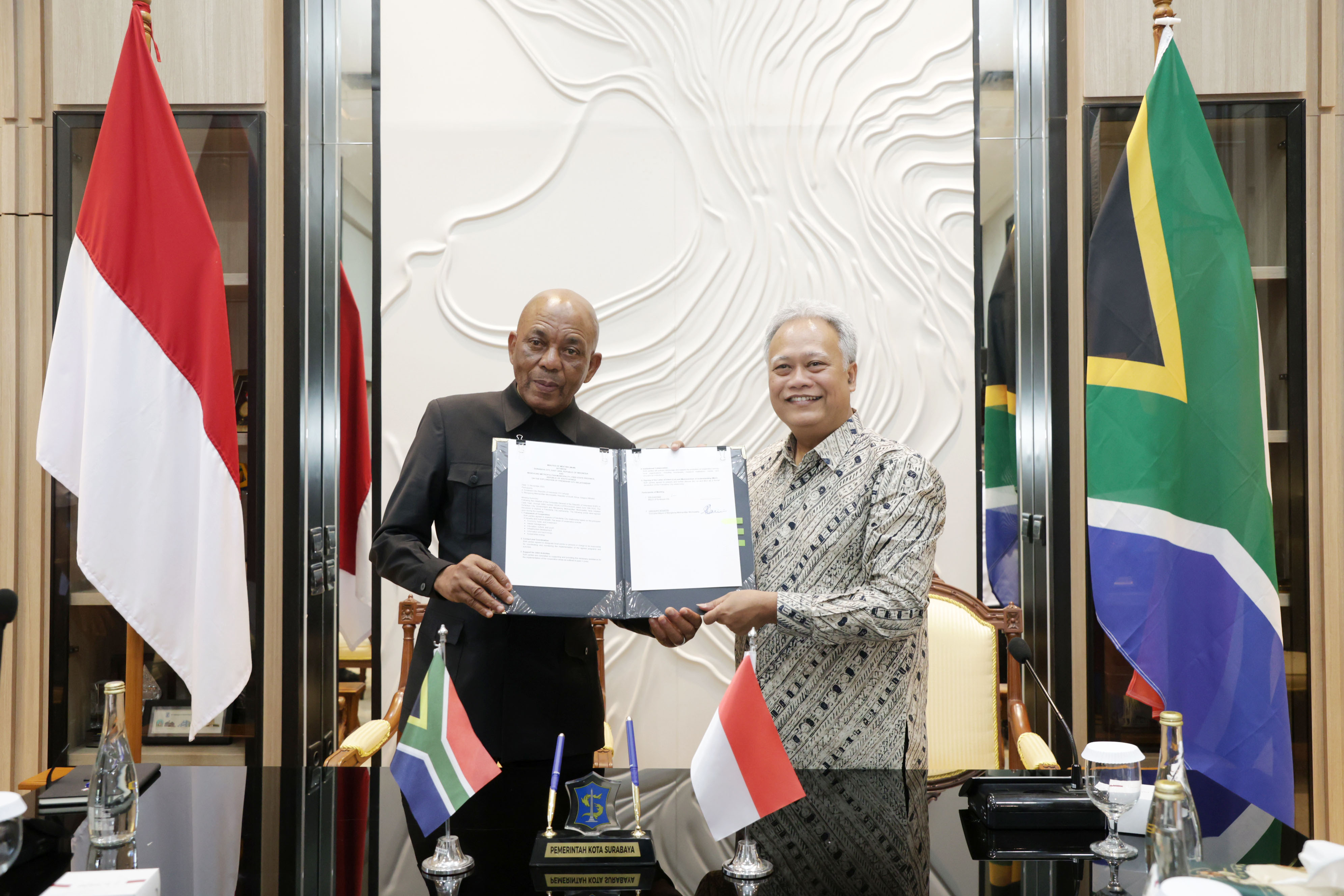Kasus demi kasus sengketa lahan — dari warga Surabaya hingga Jusuf Kalla di Makassar — menjadi cermin buram lemahnya pengawasan administrasi pertanahan di Indonesia.
Menurut Dr. Sri Setyadji, pakar hukum pertanahan dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, akar persoalan bukan sekadar pada sengketa antar pihak, melainkan pada tumpang tindih sistem hukum yang membuka ruang bagi manipulasi.
“Klaim Pertamina atas tanah yang sudah dihuni puluhan tahun menjadi problematik hukum yang menarik perhatian publik,” ujarnya, menyoroti kasus 134 hektare tanah warga Surabaya yang diklaim berdasarkan dokumen kolonial Eigendom Verponding tahun 1918, sebagaimana dikutip beritajatim (13/11).
Setyadji menegaskan, secara yuridis, hak warga jauh lebih kuat.
“Bekas hak Barat yang masa konversinya telah berakhir dan kini menjadi permukiman, hak prioritasnya ada pada masyarakat,” katanya, merujuk pada UU 86/1958, UUPA 1960, dan Keppres 32/1979 yang secara tegas mengakhiri sistem hak kolonial.
Pakar hukum pidana Hudi Yusuf dari Universitas Bung Karno menilai lemahnya pengawasan membuka peluang bagi mafia tanah menjerat siapa saja. Dia memberi contoh kasus yang kini menjerat mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kalla bersengketa dengan sebuah perusahaan yang, menurut dia, telah menyerobot tanahnya. (Kronologi konflik tanah JK bisa dibaca di sini).
“Kalau orang sekelas Jusuf Kalla bisa diserobot, apalagi rakyat kecil. Ini menunjukkan lemahnya kontrol negara,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Sementara Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti menegaskan bahwa penyerobotan tanah bukan sengketa perdata, melainkan tindak pidana. Ia menyoroti praktik kolusi antara oknum aparat dan pemodal besar yang memanipulasi sertifikat.
“Birokrasi tanah yang rumit justru menciptakan ketidakadilan struktural,” kata Fickar.
Para pakar sepakat: reformasi agraria sejati tak cukup dengan redistribusi lahan. Ia harus dimulai dari pembersihan sistem hukum dan administrasi yang masih menyisakan jejak penjajahan.